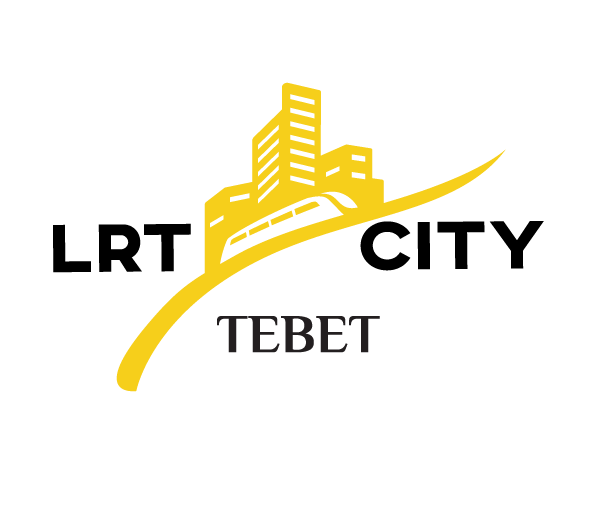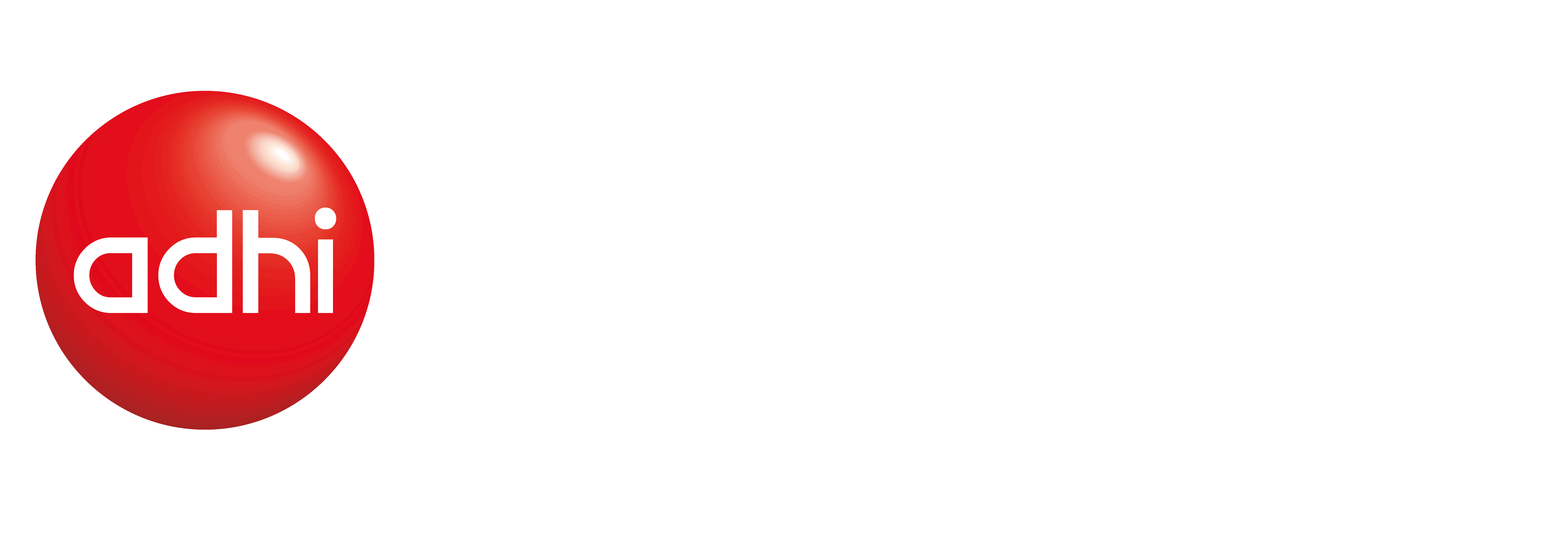Hari ini, terhitung hanya 4 kali saya memandang i-Watch di pergelangan tangan – Pada saat sampai stasiun, tengah hari jam break kantor, jam pulang kantor, dan barusan, yang terakhir, pada saat tiba di rumah.
Jarum menunjukan angka hampir pukul 10. Saya masih duduk di teras dengan kemeja rapi dan tas yang masih ada di pundak, sibuk olah nafas, berusaha merapikan senyum yang nyaris berantakan menahan emosi – di commuter line tadi ada laki-laki pecundang yang berusaha memanfaatkan situasi gerbong yang penuh sesak (you know what I mean, Right?). Saya selalu berusaha membuang energi negatif dari luar sebelum masuk ke rumah. Ya… biar vibes rumah ga ikutan negatif juga.
Sejak hari pertama kerja, saya memang tak akrab dengan rutinitas pulang-pergi kantor. Kebetulan, perusahaan tempat saya bekerja saat ini memang sudah menerapkan sistem kerja hybrid untuk beberapa level jabatan. Namun, saat ini, karena tanggung jawab (Alhamdulillah naik jabatan), suka ga suka mengharuskan saya pulang-pergi kantor 5x seminggu.
Buat saya, rutinitas commuting Jakarta-Bekasi setiap hari adalah salah satu pengalaman hidup yang paling tidak menyenangkan dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Ini cerita saya, saya juga yakin, banyak orang mengalami hal yang sama.
Namun, ternyata tak semua orang merasa kondisi ini merupakan masalah yang perlu diubah.
(What?!) Setelah saya pelajari alhasil, jawaban atas masalah ini ialah: Jakarta kekurangan hunian yang affordable dan layak pada klaster rumah kelas menengah. Berarti,
“Apakah bagi penduduk ekonomi menengah, memiliki rumah lebih penting dari memiliki kualitas hidup yang baik?”
“Apa yang membuat kepemilikan rumah adalah sebuah keharusan ditengah beberapa opsi lain seperti menyewa, co-living, dan sebagainya?”
Mari kembali pada fase saat kita awal mula bekerja, mendapatkan gaji dari perusahaan, dan mulai menetapkan tujuan-tujuan finansial. Saat itu kita tersadar bahwa pilihan selalu punya irisan. Dalam konteks hunian harga yang sesuai kemampuan-kualitas yang baik-lokasi yang strategis itu adalah sebuah ketiadaan.
Tahun 2013 saya pernah menemani saudara mencari rumah di sebuah kompleks di wilayah Bekasi. Betapa terkejutnya saya ketika mengetahui 7 dari 10 rumah yang kami survey hanya dimiliki oleh 3 orang. Artinya, setiap 1 orang memiliki 2-3 rumah di wilayah yang sama. Berusaha memahami kondisi ini malah membuat saya merasa tidak berdaya. Kita tak bisa menampik bahwa faktanya kenaikan harga rumah kelas menengah tidak selaras dengan kenaikan penghasilan. Kelas menengah harus struggling mati-matian untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang ideal.
Sungguh ironi, bukan?
Dari motivasi saja sudah jauh berbeda. Kelas menengah menjadikan rumah hanya sebagai memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan kelas atas membeli rumah sebagai sarana menambah portofolio investasi dan aset.
Lantas? Apakah kita harus menyerah dengan keadaan? Tak bisakah kita mempunyai tempat tinggal yang selaras dengan kualitas hidup?
Jakarta Pada Data

Jakarta adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di wilayah Asia Tenggara. Arus urbanisasi telah melebarkan batas area perkotaan ke kota-kota tetangga menjadikannya salah satu wilayah aglomerasi terbesar di dunia. Ya, yang kita kenal sekarang adalah Jabodetabek.
Saat ini Jakarta juga sudah menjadi “rumah” bagi 10.6 juta penduduknya. Meskipun begitu, Jakarta masih didominasi sebagai daerah perumahan yang rendah meskipun kepadatannya yang tinggi. Hanya 40% dari wilayah Jakarta yang diatur sebagai area perumahan dan didominasi oleh rumah-rumah tapak berupa kampung deret padat penduduk di gang-gang kecil.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 38% dari rumah yang tersedia di Jakarta ditempati oleh penyewa. Kita tau, masalah hunian di Jakarta saat ini hanya berputar pada masalah ketersediaan dan permintaan. Ketidakseimbangan inilah yang menjadikan harga hunian kian hari kian tak terkejar isi kantong.
Namun, pergerakan harga yang signifikan hanya terjadi pada rumah tapak pada segmen menengah, sedangkan harga untuk segmen rumah mewah, apartemen, dan rusun cenderung stabil.
Visualisasi Akan Rumah


Tidak muluk-muluk. Saya ingin tinggal di hunian yang dapat meng-cover mobilitas dan produktivitas. Selesai solat subuh masih bisa produktif di rumah atau sekadar menjalani hobi baca buku sambil ngopi. Saya ingin bebas dari perasaan di kejar oleh waktu karena harus bangun, siap-siap, dan berangkat ke stasiun secepat mungkin supaya bisa dapat duduk di commuter line atau setidaknya tiba on-time di kantor.
Saya ingin tinggal di area yang dekat dengan kantor dengan fasilitas penunjang yang lengkap seperti rumah sakit, transportasi umum, dan sarana hiburan. Cukup jalan kaki, mayoritas kebutuhan saya bisa terpenuhi.
Saya ingin antar istri ke kantor dan anak ke sekolah, pulang kerja masih bisa spending waktu buat hal-hal personal yang saya suka, dan yang paling penting, saya ingin punya waktu lebih bersama keluarga. Kondisi commuting yang saya jalani sekarang membuat saya merasa kehilangan (waktu untuk) keluarga.
Tak terbatas tipologi – mau rumah tapak ataupun apartemen.
Tak terbatas status – sewa ataupun beli, asal kemampuan dan proyeksi finansial saya dapat bertemu dengan harga yang cocok.
Pun, bagi saya rumah bukanlah instrumen investasi. Meskipun, betul bahwa rumah termasuk dalam golongan “aset”. Tapi, terkadang kita abai. Memaksakan untuk tinggal di rumah tapak di ujung kota penyangga melahirkan intangible cost yang luput dari hitungan.
Kesehatan jasmani & rohani, kualitas hidup, dan waktu
Layakkah semua itu dikorbankan?
Saat ini saya duduk di meja kerja, untuk mengingatkan saya sendiri agar mengembalikan rumah pada makna hakikatnya, yaitu:
Perasaan.